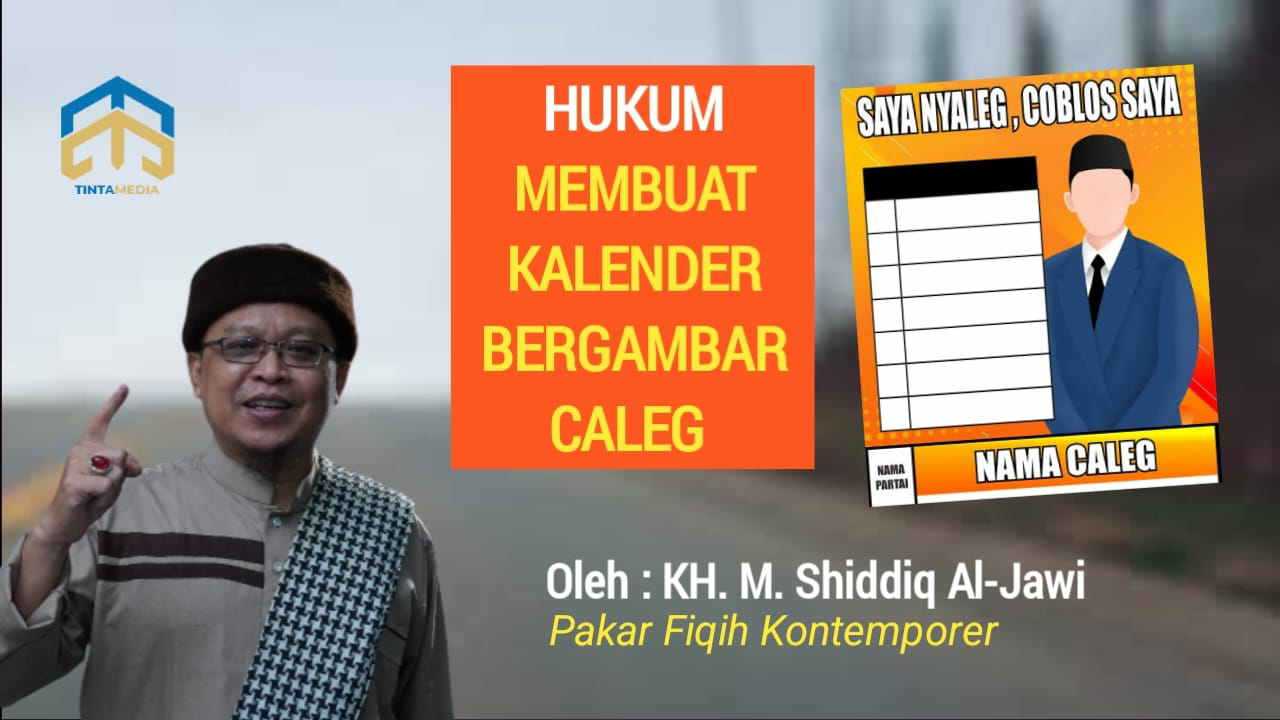Sabtu, 06 Juli 2024
Kamis, 18 April 2024
Politik Industri Negara Khilafah
Soal:
Tinta Media - Apa makna “industri dengan jenis-jenisnya dibangun di atas asas politik perang”? Misal apa yang dinyatakan di dalam Kitab Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fî al-Hukmi wa al-Idârah: “Industri dengan jenis-jenisnya wajib dibangun di atas asas politik perang.” Adakah contohnya?
Jawab:
Jawabannya ada pada Kitab Ajhizah halaman 108 file word. Demikian juga pada Kitab Muqaddimah ad-Dustûr (I/132) file word. Berikut kutipannya:
Karena Daulah Islamiyah merupakan negara yang mengemban dakwah Islamiyah melalui metode dakwah dan jihad, maka negara harus selalu siap untuk melakukan jihad. Ini menuntut industri di negara, industri berat atau ringan, dibangun di atas asas politik perang. Dengan begitu, jika diperlukan untuk mengubahnya ke industri yang menghasilkan industri perang dengan jenis-jenisnya, maka mudah bagi negara melakukan hal itu kapan saja diinginkan.
Oleh karena itu semua industri di dalam Negara Khilafah wajib dibangun di atas asas politik perang. Semua pabrik, baik yang menghasilkan industri berat atau menghasilkan industri ringan, dibangun di atas asas politik ini. Tujuannya untuk memudahkan pengalihan produksinya ke produksi perang kapan saja negara memerlukan hal itu.
Artinya, semua pabrik di dalam Negara Khilafah harus dibuat ke arah yang sedemikian rupa memungkinkan roda produksinya dapat dengan mudah dialihkan untuk menghasilkan produk-produk yang berkaitan dengan aspek militer yang tidak diproduksi dalam kondisi normal. Misalnya, jika ada pabrik kendaraan sipil maka harus dibangun sedemikian rupa yang memungkinkan dari aspek teknis dan praktis untuk mengalihkan roda produksi di situ untuk membuat kendaraan militer yang digunakan oleh negara dalam perang melawan orang-orang kafir. Misal lain, jika ada pabrik pakaian, maka harus dibuat sedemikian rupa yang memungkinkan produksinya dapat dengan mudah dialihkan menjadi pembuatan pakaian militer. Begitulah. Kebijakan (politik) pembangunan pabrik didasarkan pada politik perang dalam hal roda produksi, bangunan pabrik, dan dalam kemungkinan mencegah pemogokan di dalamnya, juga dalam kemungkinan bekerja di dalamnya di gedung bawah tanah, dll; di antara hal-hal yang ditentukan oleh para ahli dan disupervisi oleh negara.
[Dikutip dari Jawab-Soal Syaikh Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah tanggal 15 Muharram 1445 H – 02 Agustus 2023 M]
*Sumber:*
https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/90192.html
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/839403611080343
https://alwaie.net/fikih/politik-industri-negara-khilafah/
Selasa, 09 April 2024
Bolehkah Sholat dan Berkhutbah Idul Fitri pada Tanggal 2 Syawal?
Tanya :
Tinta Media - Ustadz, bolehkah seseorang yang sudah sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal, lalu sholat lagi, atau berkhutbah Idul Fitri pada tanggal 2 Syawal?
Jawab :
Tidak boleh hukumnya sholat atau berkhutbah Idul Fitri pada tanggal 2 Syawal, karena batas akhir sholat dan khutbah Idul Fitri adalah waktu zawal (awal waktu Zhuhur) pada tanggal 1 Syawal itu.
Dalil bahwa batas akhir sholat Idul Fitri adalah waktu zawal, ditunjukkan oleh hadits berikut ini :
عن أبي عُميرِ بنِ أنسِ بنِ مالكٍ، قال: حدَّثني عُمومتي، من الأنصارِ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالوا: أُغْمَي علينا هلالُ شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاءَ ركبٌ من آخِر النهار، فشهِدوا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم رأوُا الهلالَ بالأمس، فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُفطِروا، وأنْ يَخرُجوا إلى عيدِهم من الغدِ
Dari Abu 'Umair bin Anas bin Malik RA, dia berkara,"Telah meriwayatkan kepadaku paman-pamanku dari golongan Anshar dari para shahabat Rasulullah SAW, bahwa mereka berkata,'Telah tertutup awan bagi kami hilal Syawal, maka pada pagi harinya kami tetap berpuasa. Datanglah kemudian satu rombongan pada sore hari, dan mereka pun bersaksi kepada Nabi SAW bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berbuka, dan juga memerintahkan untuk sholat Idul Fitri pada keesokan harinya." (HR Ahmad, no. 20.603; Al Baihaqi, dalam _As-Sunan Al-Kubra_, 3/316; hadits ini dinilai shahih oleh Imam Syaukani dalam _As-Sailul Jarrar_, 1/291; dan oleh Syekh Al-Albani dalam _Shahih Sunan Ibnu Majah_, no. 1348).
Lihat : https://dorar.net/feqhia/1716/
Hadits tersebut menunjukkan bahwa jika informasi rukyatul hilal datangnya pada waktu sore hari _(akhir an nahar),_ yakni berarti sudah melampaui waktu zawal (awal waktu Zhuhur), maka sholat Idul Fitrinya tidak dapat lagi dilaksanakan pada hari itu (tanggal 1 Syawal), melainkan dilaksanakan pada keesokan harinya (tanggal 2 Syawal).
Ini berarti batas akhir sholat Idul Fitri adalah tibanya waktu zawal (waktu awal Zhuhur) pada tanggal 1 Syawal.
Demikianlah menurut kesepakatan (ijma') para ulama, yakni tak ada khilafiyah di antara mereka dalam masalah ini.
Imam Ibnu Hazm berkata :
واتَّفقوا أنَّ من صفاء الشمس إلى زوالها وقتٌ لصلاة العيدين على أهل الأمصار ((مراتب الإجماع)) (ص: 32).
"Para ulama sepakat bahwa sejak matahari bersinar terang hingga zawal-nya matahari (awal waktu Zhuhur) adalah waktu untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha bagi penduduk kota." (Ibnu Hazm, _Maratibul Ijma',_ hlm. 32).
Ibnu Rusyd berkata :
واتَّفقوا على أنَّ وقتها... إلى الزوال . ((بداية المجتهد)) (1/229).
"Para ulama sepakat bahwa waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha...adalah hingga waktu zawal (awal waktu Zhuhur)." (Ibnu Rusyd, _Bidayatul Mujtahid,_ 1/229).
Imam Syarbaini Khathib berkata :
وأمَّا كون آخر وقتها- أي: صلاة العيد- الزوال، فمُتَّفق عليه ((مغني المحتاج)) (1/310).
"Adapun bahwa batas akhir sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah waktu zawal (waktu awal Zhuhur), maka itu sudah disepakati ulama." (Syarbaini Khathib, __Mughni al-Muhtaj,_ 1/310).
Imam Syaukani berkata :
وقال بعضُ العلماء: وهي من بعد انبساطِ الشَّمس إلى الزوال، ولا أعرِف فيه خلافًا ((الدَّراري المضية)) (1/118).
"Sebagian ulama berkata,'[waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha] adalah sejak terangnya sinar matahari hingga zawal (awal waktu Zhuhur), dan saya tidak melihat ada khilafiyah dalam masalah ini." ( _Ad-Darari al-Mudhi'ah,_ 1/118).
(Lihat : https://dorar.net/feqhia/1716/).
Dari kutipan-kutipan tersebut, jelaslah bahwa batas akhir waktu sholat Idul Fitri adalah tibanya waktu zawal (waktu awal Zhuhur) pada tanggal 1 Syawal.
Jadi, kalau seseorang meyakini hari Ahad kemarin adalah tanggal 1 Syawal, maka tidak boleh pada hari Senin ini, yakni tanggal 2 Syawal, dia sholat atau berkhutbah Iedul Fitri. Yang demikian itu karena berarti dia telah sholat atau berkhutbah Idul Fitri pada waktu yang telah melampaui waktu yang disyariatkan, yaitu sejak matahari bersinar terang (waktu Dhuha) hingga waktu zawal (awal waktu Zhuhur) pada tanggal 1 Syawal.
Kecuali jika dia memperoleh info rukyatul hilal yang datang terlambat melampaui waktu zawal (waktu awal Zhuhur) tanggal 1 Syawal, misal pukul 14.00 WIB atau pukul 17.00 WIB tanggal 1 Syawal, maka dia boleh sholat dan berkhutbah Idul Fitri pada tanggal 2 Syawal.
Dalil kebolehannya adalah hadits dari Abu 'Umair bin Anas bin Malik RA yang sudah kami kutip di atas, bahwa Nabi SAW memperoleh kesaksian rukyatul hilal baru pada sore hari tanggal 1 Syawal. Maka kemudian Nabi SAW lalu memerintahkan untuk berbuka saat itu juga, dan juga memerintahkan untuk sholat Idul Fitri pada keesokan harinya (tanggal 2 Syawal). (https://dorar.net/feqhia/1716/).
Kesimpulannya, tidak boleh hukumnya sholat atau berkhutbah Idul Fitri pada tanggal 2 Syawal, karena batas akhir sholat dan khutbah Idul Fitri adalah waktu zawal (awal waktu Zhuhur) pada tanggal 1 Syawal.
Memang ada sebagian ulama yang membolehkan sholat dan berkhutbah Idul Fitri pada tanggal 2 Syawal, dengan alasan ada hadits-hadits yang menunjukkan bolehnya melaksanakan shalat yang sama dua kali.
Di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:
Dalil pertama, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ghundar berkata, dia telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Amru berkata, Aku mendengar Jabir bin ‘Abdullah berkata, "Mu’adz bin Jabal pernah shalat bersama Nabi SAW dia lalu kembali pulang dan mengimami kaumnya shalat ‘Isya “ (HR Bukhari, no. 660).
Dalil kedua, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu ‘Ajlan, dia telah menceritakan kepadaku ‘Ubaidullah Bin Muqsim dari Jabir bin Abdullah, "Sesungguhnya Muadz bin Jabal sholat Isya’ bersama Rasulullah SAW, kemudian mendatangi kaumnya lalu sholat menjadi imam mereka sholat Isya’ juga”. (HR Ahmad, no. 13723)
Dalil ketiga, telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ma’n bin Isa dari Sa’id bin As-Sa`ib dari Nuh bin Sha’sha’ah dari Yazid bin Amir dia berkata,"Saya pernah datang ke Masjid sementara Nabi SAW dalam keadaan shalat. Saya lalu duduk dan tidak shalat bersama mereka. Lalu Rasulullah SAW pergi dan melihat Yazid sedang duduk. Beliau bersabda: “Apakah kamu belum masuk Islam wahai Yazid?” Dia menjawab,"Tentu wahai Rasulullah, saya telah masuk Islam." Rasulullah SAW bersabda,“Lalu apa yang menghalangimu untuk shalat bersama jama’ah?” Dia menjawab,"Saya telah shalat di rumahku dan saya menyangka kalian telah selesai shalat. Maka beliau bersabda: “Apabila kamu datang ke shalat jama’ah, lalu kamu mendapati orang-orang sedang shalat, maka shalatlah bersama mereka, meskipun kamu telah shalat, shalatmu itu sebagai nafilah (shalat sunnah) bagimu, dan yang ini (yang sebelumnya) menjadi yang wajib.” (HR Abu Daud, no. 489; Ahmad, no. 18209).
Demikianlah sebagian dalil yang dikemukakan ulama yang membolehkan sholat dan berkhutbah Idul Fitri pada tanggal 2 Syawal, dengan alasan dari hadits-hadits itu dapat diistinbath hukum syara' umum, yaitu boleh hukumnya melaksanakan shalat yang sama dua kali.
Jawaban kami adalah, dalil-dalil tersebut tidak dapat menjadi dalil bolehnya sholat Idul Fitri pada tanggal 2 Syawal, karena hadits-hadits tersebut topiknya (maudhu'-nya) khusus berkaitan dengan *sholat wajib lima waktu*, bukan berkaitan dengan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha.
Tidak dapat diistinbath dari hadits-hadits tersebut suatu hukum umum bahwa boleh hukumnya sholat yang sama dilakukan dua kali, kecuali sholat lima waktu, karena maudhu' (topik) hadits-hadits tersebut berkaitan dengan *sholat wajib lima waktu*, seperti sholat Isya', sebagaimana nampak jelas pada _sababul wurud_ untuk hadits pertama dan hadits kedua.
Adapun generalisasi hadits-hadits tersebut dari lafal-lafal umumnya hingga mencakup sholat di luar sholat waktu, seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak dapat diterima.
Kaidah ushul fiqih dalam masalah ini menyebutkan :
عموم اللفظ في خصوص السبب هو عموم في موضوع الحادثة و السؤال وليس عموما في كل شيء
"Keumuman kata (lafal) berdasarkan sebab yang khusus, hanyalah berlaku umum untuk topik (maudhu') dalam peristiwa dan pertanyaan (yang menjadi sababul nuzul ayat atau sababul wurud hadits), tidak dapat diambil kesimpulan hukum umum untuk segala sesuatu." (Taqiyuddin An-Nabhani, _al-Syakhshiyah Al-Islamiyah,_ 3/243).
Dengan demikian, hadits-hadits di atas hanya dapat diberlakukan untuk sholat wajib yang lima waktu, tidak dapat diberlakukan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha.
Maka dari itu, kalau seseorang meyakini hari Ahad kemarin adalah 1 Syawal, tidak boleh pada hari Senin ini yakni 2 Syawal, dia sholat atau berkhutbah Iedul Fitri.
Kecuali jika dia memperoleh info rukyatul hilalnya terlambat melampaui waktu zawal (awal waktu Zhuhur) tanggal 1 Syawal, misal pukul 14.00 atau 17.00 tanggal 1 Syawal, maka dia boleh sholat dan berkhutbah Idul Fitri pada tanggal 2 Syawal. Wallahu a'lam.
Yogyakarta, 2 Syawal 1443 / 2 Mei 2022
M. Shiddiq Al Jawi
Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi (Pakar Fikih Muamalah)